Bahasa Krisis dan Diplomasi Hukum: Membaca Sinyal di Balik OTT Kepala Daerah
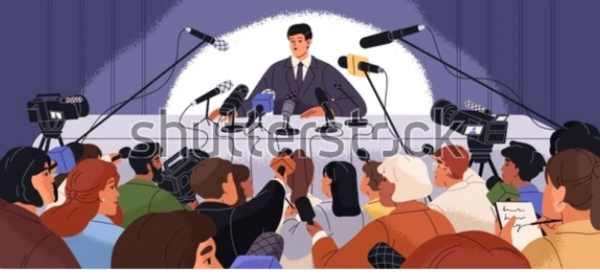
Foto Ilustrasi. Dok foto( Red)
Oleh : Rudi Syaf Putra, SE., M.Ak., Ak., ACFI., CFrA., CBV., CACP., ACPA., CTA
Dosen Audit Forensik Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI)
SIGAPNEWS.CO.ID | Pekanbaru - Ketika publik mendengar kabar adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, reaksi pertama biasanya muncul bukan dari lembaga hukum, melainkan dari pejabat daerah. Ungkapan seperti “hanya dimintai keterangan,” “bukan tersangka,” atau “sekadar klarifikasi” segera mengisi ruang berita. Kalimat-kalimat itu terdengar menenangkan, tetapi dalam konteks komunikasi publik, justru menyimpan pesan yang lebih dalam: pemerintah sedang berupaya mengendalikan persepsi krisis.(4/11)
Dalam kasus OTT yang terjadi di berbagai daerah, termasuk yang baru-baru ini ramai di Riau, bahasa semacam ini menjadi tameng diplomatis yang umum digunakan. Masyarakat mungkin menafsirkan pernyataan tersebut sebagai tanda bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, bagi mereka yang memahami pola krisis birokrasi, pernyataan ini lebih sering merupakan strategi komunikasi politik ketimbang penjelasan hukum.
*Diplomasi Krisis dan Strategi Bahasa*
Dalam teori komunikasi krisis (Benoit, 1997), dikenal konsep denial strategy dan diminishment strategy. Pemerintah menggunakan bentuk komunikasi ini untuk mereduksi persepsi kesalahan atau tanggung jawab, dengan tujuan menjaga stabilitas sosial-politik sementara fakta hukum masih berjalan. Strategi ini tidak sepenuhnya salah; ia seringkali efektif untuk menenangkan publik dan menjaga kepercayaan jangka pendek.
Namun, risiko muncul ketika “bahasa krisis” digunakan berlebihan tanpa diikuti transparansi. Publik bisa kehilangan kepercayaan bukan hanya kepada individu yang terlibat, tetapi juga kepada institusi yang berupaya menutupi situasi. Di titik ini, krisis komunikasi justru berubah menjadi krisis integritas.
Dalam konteks Indonesia, bahasa krisis sering dipakai untuk membeli waktu politik. Ketika seorang pejabat disebut “hanya dimintai keterangan,” biasanya aparat daerah sedang berusaha menjaga citra kelembagaan, sekaligus mengantisipasi dampak domino di tingkat lokal. Namun publik yang kritis akan memahami: KPK tidak melakukan OTT hanya untuk meminta keterangan. OTT adalah tindakan penegakan hukum berdasarkan real-time evidence yang sudah terverifikasi.
*Audit Forensik dan Transparansi Awal*
Dalam praktik audit forensik, dikenal prinsip initial disclosure — bahwa transparansi tahap awal adalah kunci untuk mencegah rumor yang merusak kredibilitas institusi.
Jika pemerintah daerah bersikap terbuka sejak awal, potensi spekulasi publik bisa ditekan.
Namun, ketika informasi disembunyikan di balik kalimat ambigu, rumor berkembang lebih cepat daripada klarifikasi resmi.
Inilah yang disebut dalam audit governance sebagai informational vacuum, yaitu kekosongan data yang diisi oleh persepsi publik.
Sebuah pemerintahan yang sehat seharusnya tidak hanya siap menghadapi pemeriksaan keuangan, tetapi juga siap diaudit dalam hal kejujuran berbahasa.
Bahasa publik yang tidak akurat bisa berimplikasi pada rusaknya akuntabilitas moral.
*Klarifikasi atau OTT: Memahami Perbedaan Konteks*
Secara hukum, OTT adalah tindakan penangkapan terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan bukti langsung.
Sementara klarifikasi adalah kegiatan administratif untuk memperjelas suatu informasi.
Dua istilah ini tidak bisa dipertukarkan.
Mengatakan OTT sebagai klarifikasi sama saja dengan menyamakan penyelidikan pidana dengan wawancara informal.
Pernyataan seperti ini memang terdengar menenangkan, tetapi secara forensik dan hukum, itu menyesatkan publik.
Oleh karena itu, pejabat daerah perlu berhati-hati dalam memberikan pernyataan publik.
Dalam audit forensik, salah satu prinsip utama adalah “no misleading statement.”
Artinya, kebenaran tidak hanya diukur dari isi, tetapi juga dari konteks dan dampaknya terhadap persepsi publik.
*Etika Komunikasi Pemerintahan*
Dalam tata kelola modern, komunikasi publik bukan hanya urusan kehumasan — ia bagian dari governance integrity.
Bahasa yang digunakan pemerintah mencerminkan nilai-nilai transparansi dan tanggung jawab.
Ketika pejabat berbicara dengan jujur dan proporsional, publik akan memahami bahwa sistem sedang bekerja, bukan disembunyikan.
Sebaliknya, ketika bahasa menjadi alat pertahanan, kepercayaan publik mulai menipis.
Maka, setiap lembaga pemerintahan seharusnya memiliki pedoman komunikasi krisis yang berlandaskan etika, bukan kepanikan.
Prinsip ethical communication mengajarkan bahwa dalam situasi genting, yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan aman, tetapi kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
*Penutup: Saatnya Bahasa Publik Diaudit*
OTT terhadap pejabat publik, siapapun itu, selalu menjadi ujian moral bagi pemerintahan dan masyarakat.
Namun yang sering terlupakan, krisis terbesar bukan hanya tentang siapa yang ditangkap, melainkan bagaimana pemerintah berbicara saat kebenaran sedang diuji.
Dalam dunia audit forensik, ada pepatah lama:
“Bukti bisa dibersihkan, tapi bahasa tak bisa dihapus.”
Bahasa adalah jejak moral dari integritas seseorang maupun institusi.
Karena itu, sudah saatnya pemerintah belajar bahwa yang perlu dijaga bukan hanya angka dalam laporan, tapi juga kejujuran dalam kata-kata.
Editor :Erick Donald Simanjuntak
Source : Rudi Syaf Putra, SE., M.Ak., Ak., ACFI., CFrA., CBV., CACP., ACPA., CTA




























